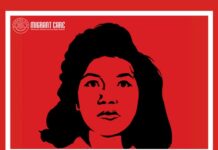Tanggal 15 Agustus ini menandai peringatan 20 tahun penandatanganan perjanjian damai Aceh yang mengakhiri tiga dekade perang separatis di provinsi paling barat Indonesia.
Perjanjian damai Aceh itu dikenal sebagai Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki, memiliki dua keunggulan. Pertama, tidak seperti banyak perjanjian damai yang akhirnya runtuh, MoU tersebut tetap utuh.
Keunggulan kedua, MoU Helsinki ini berasal dari pelajaran yang diberikannya bagi proses resolusi konflik lainnya. Aturan pertama negosiasi adalah jika perang adalah politik dengan cara lain, maka negosiasi untuk mengakhiri perang bersifat sangat politis, baik bagi masing-masing pihak dengan konstituen domestiknya maupun antara pihak-pihak yang bernegosiasi.
Aturan kedua resolusi konflik adalah bahwa pihak-pihak yang berkonflik harus menginginkan konflik berakhir. Di Ukraina dan Jalur Gaza, setidaknya salah satu pihak tidak tertarik untuk benar-benar bernegosiasi saat ini.
Demikian pula, terdapat sejumlah perundingan dalam perang Sri Lanka dengan Macan Tamil, tetapi perundingan tersebut kurang memiliki komitmen politik dari kedua belah pihak. Hal ini mengakibatkan pemerintah akhirnya menghancurkan Macan Tamil, dengan sekitar 40.000 warga sipil terbunuh di minggu-minggu terakhir kampanyenya –sebuah pelajaran alternatif yang tampaknya juga dirasakan di tempat lain.
Yang membuat suatu konflik “matang” untuk resolusi yang dinegosiasikan adalah ketika tidak ada pihak yang dapat mengalahkan pihak lain secara meyakinkan dan biaya perang yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak melebihi manfaat yang mungkin diperoleh. Hal ini disebut sebagai “kebuntuan yang menyakitkan”.
Baca juga: 2 Dekade Damai, Aceh Masih Hadapi Tantangan Serius
Di Pulau Mindanao, Filipina, separatis yang telah lama berkuasa bersama Front Pembebasan Islam Moro tidak dapat dimenangkan secara militer oleh kedua belah pihak, namun terus menguras sumber daya dan rakyat dari keduanya, mendorong kedua belah pihak menuju perdamaian.
Demikian pula, perang revolusioner Kolombia berakhir ketika, setelah 50 tahun, tidak ada pihak yang dapat membuat kemajuan, seperti yang juga terjadi dalam perang saudara El Salvador. Dalam bentrokan perbatasan antara India dan Pakistan yang bersenjata nuklir, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri pertempuran, menyadari bahwa jika salah satu pihak menang, pihak yang kalah kemungkinan akan menggunakan senjata nuklir, yang akan menciptakan kebuntuan jenis yang berbeda.
Faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap keberhasilan negosiasi dapat mencakup perubahan kepemimpinan politik di mana terdapat komitmen yang lebih rendah terhadap tujuan awal perang (perang Ukraina kemungkinan akan berakhir dengan negosiasi yang sesungguhnya jika
Vladimir Putin meninggalkan panggung politik; di mana tujuan awal telah hilang dalam “kabut perang”; di mana bencana alam memperkenalkan prioritas baru yang mendesak seperti tsunami Samudra Hindia 2004; dan di mana terdapat intervensi eksternal atau tekanan dari negara atau kelompok negara lain.
Pihak eksternal juga dapat menawarkan bujukan untuk menghentikan pertempuran, seperti rekonstruksi, bantuan, dan investasi, dan juga dapat bertindak sebagai mediator netral dalam proses negosiasi, seperti Qatar dalam perang Gaza, serta menjadi penjamin bahwa setiap kesepakatan yang dicapai akan dihormati.
Masalah utama dalam negosiasi perdamaian adalah tidak semua orang ingin melihatnya berhasil; sebagian besar negosiasi memiliki “pengganggu” seperti itu. Oleh karena itu, agar negosiasi berhasil, sangat penting bahwa kedua belah pihak harus memiliki monopoli politik di pihak mereka masing-masing, termasuk kemampuan untuk menetralisir pihak-pihak yang mengganggu.
Jika konflik terjadi atas wilayah dalam suatu negara, misalnya, wilayah Donbas di Ukraina, atau kendali negara yang efektif, seperti wilayah Palestina, mungkin perlu ada kesepakatan untuk melegalkan partai politik yang dilarang dan pembentukan wilayah otonom yang secara efektif berpemerintahan sendiri di dalam negara yang memayunginya.
Dengan asumsi kesepakatan dapat dicapai, metode dasar implementasi adalah melalui pengaturan transisi yang berurutan, atau melalui semuanya sekaligus. Masalah dengan yang pertama adalah memungkinkan banyak titik di mana implementasi kesepakatan dapat gagal; masalah dengan yang kedua adalah bahwa mengelola semua aspek kesepakatan secara bersamaan dapat membebani kapasitas organisasi.
Lebih dari itu, negosiasi bukanlah tentang masing-masing pihak mendapatkan semua yang mereka inginkan, tetapi tentang apa yang dapat mereka terima. Akan bermanfaat juga jika masing-masing pihak tidak memikirkan tuntutan publik mereka, tetapi substansi apa yang mereka butuhkan dan kemudian mengupayakannya. Pada akhirnya, 50% dari sesuatu selalu lebih baik daripada 100% dari ketiadaan.
Jika kedua belah pihak dapat menemukan titik-titik kesepakatan yang sejati, masing-masing pihak mungkin dapat meningkatkan manfaat perdamaian lebih dari sekadar setengahnya. Dengan cara ini, totalitas kesepakatan yang baik dapat, secara fungsional, lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya.
Namun, meskipun segala sesuatunya mendukung, negosiasi untuk mengakhiri perang secara permanen bukanlah apa-apa jika bukan proses yang sangat rumit dan berlapis-lapis yang melibatkan banyak bagian yang bergerak, yang pada gilirannya, secara inheren rentan terhadap kegagalan. Hanya dengan keadaan yang mendesak dan komitmen untuk menemukan hasil, yang dikelola dengan cermat oleh kedua belah pihak serta mediator, keberhasilan dapat dicapai.
Tetaplah instruktif bahwa, setelah setelah perundingan selama x bulan, kesepakatan damai Aceh akhirnya tercapai dengan seorang mediator yang terampil dan kedua belah pihak mencapai kompromi yang nyata.
11 Agustus 2025.
Damien Kingsbury, Profesor Emeritus, Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial, Universitas Deakin; penulis buku ‘‘Politik di Asia Tenggara Kontemporer: Otoritas, Demokrasi, dan Perubahan Politik’, Routledge, dan ‘Asia Tenggara: Profil Politik’, Oxford UP. Artikel ini disalin dari jurnal yang tayang di Pearls and Irritations.