Aceh, tanah yang kaya akan sejarah, budaya, dan sumber daya alam, seharusnya menjadi salah satu daerah paling makmur di Indonesia.
Namun, realita berbicara lain. Perekonomian Aceh tetap tertinggal, dan sebagian besar masyarakatnya masih terjebak dalam kemiskinan. Ini bukan karena kurangnya potensi, tetapi lebih kepada bagaimana Aceh dikelola.
Kenyataan pahit ini bukan lagi rahasia, melainkan kebohongan yang nyata—kebohongan yang diciptakan dan diterima begitu saja oleh banyak pihak.
Salah satu masalah mendasar yang terus berulang adalah perputaran uang yang sangat singkat di Aceh. Sumber utama pergerakan ekonomi di daerah ini hanya bertumpu pada APBA yang didanai oleh pemerintah pusat.
Uang yang masuk ke Aceh tak bertahan lama, dalam waktu kurang dari seminggu, mayoritas sudah mengalir keluar, terutama ke Sumatera Utara. Aceh seperti mesin cuci di sebuah laundry: uang mampir sebentar, lalu pergi lagi setelah bersih.
Kondisi ini diperparah oleh kebiasaan masyarakat Aceh yang lebih senang berbelanja di luar daerah, terutama ke Medan. Kemudahan akses kredit dari lembaga leasing berbasis di luar Aceh mempercepat aliran dana keluar.
Baca juga: Neraca Perdagangan Aceh Defisit Parah
Ditambah lagi, banyak kendaraan berplat BK yang bebas berlalu lalang di Aceh, yang secara tidak langsung mengalirkan pendapatan pajak kendaraan ke Sumut.
Menghadapi realitas ini, muncul pertanyaan besar: mengapa Aceh tidak berusaha mempertahankan uangnya lebih lama di dalam daerah? Jawabannya sederhana: Aceh tidak memiliki industri yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri.
Hampir semua barang kebutuhan didatangkan dari luar, membuat uang terus mengalir ke daerah lain.
Solusi paling logis adalah membangun pabrik-pabrik yang mampu memproduksi barang yang selama ini didatangkan dari luar. Jika Aceh memiliki industri sendiri, uang akan terus berputar di dalam daerah dan bahkan bisa menarik pemasukan dari luar jika produk-produknya berkualitas dan kompetitif.
Selain industri, sektor pariwisata seharusnya menjadi salah satu cara bagi Aceh untuk mempertahankan uang dan mengundang lebih banyak pendapatan dari luar. Keindahan alam Aceh tak diragukan lagi.
Namun, sekadar keindahan saja tidak cukup. Pariwisata harus dikelola dengan serius dan profesional, tidak hanya mengandalkan pemandangan, tetapi juga memberikan pengalaman menarik bagi wisatawan.
Aceh perlu lebih kreatif dalam menciptakan destinasi wisata baru, membangun infrastruktur yang lebih baik, serta membentuk ekosistem yang mendukung industri pariwisata, termasuk oleh-oleh khas yang dapat menjadi daya tarik tersendiri.
Namun, semua ini kembali pada mentalitas dan pola pikir masyarakat Aceh sendiri. Masihkah ada orang yang benar-benar peduli untuk membangun Aceh? Atau justru banyak yang lebih nyaman menikmati simbol-simbol politik tanpa substansi yang nyata?
Jika kebanggaan Aceh hanya berkutat pada bendera, UUPA, atau kemenangan dalam pilkada, tanpa ada usaha nyata untuk membangun ekonomi, maka Aceh memang sedang hidup dalam kebohongan yang nyata.
Saatnya berhenti mencari kambing hitam dan mulai bertindak. Jika Aceh ingin keluar dari ketertinggalan, maka diperlukan kerja nyata, bukan sekadar wacana. Jika ada kemauan, pasti ada jalan. Aceh tidak kekurangan sumber daya, tetapi kekurangan niat dan keseriusan untuk berubah.












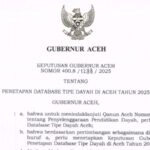
> maka Aceh memang sedang hidup dalam kebohongan yang nyata.
Memang sejak kapan Aceh tidak hidup dalam kebohongan? Terlalu bangga dengan Aceh jaman nenek moyang 1600-an. Terlalu bangga dengan bahasa Aceh, tapi nulis diakritik aja nggak bisa. dan kebohongan-kebohongan lain seperti ACEH (Arab, Cina, Eropa, Hindi)