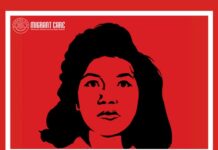Aceh, tanah yang dikenal dengan syariat, adat, dan kekayaan budayanya, pernah menjadi saksi bisu dari salah satu konflik bersenjata paling lama dalam sejarah Indonesia. Di balik senyum ramah masyarakatnya hari ini, tersimpan kenangan pahit yang tak bisa begitu saja dihapus: masa ketika Aceh dinyatakan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).
Bagi sebagian orang, istilah DOM mungkin hanya sebuah bagian dari pelajaran sejarah. Tapi bagi banyak rakyat Aceh, terutama yang hidup di era 1989-1998, DOM adalah kenangan yang begitu hidup — tentang ketakutan, kehilangan, dan ketidakpastian.
Patroli militer di setiap sudut desa, suara tembakan yang tiba-tiba, razia yang tak pandang waktu, dan orang-orang yang “hilang” tanpa penjelasan — semua menjadi bagian dari realitas sehari-hari.
Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah pusat bukanlah sekadar perang ideologi. Ia tumbuh dari luka lama, dari rasa tidak adil yang dipendam bertahun-tahun.
Sayangnya, dalam setiap konflik bersenjata, pihak yang paling menderita hampir selalu sama: masyarakat sipil. Mereka yang tidak memegang senjata, tapi harus menanggung akibatnya. Mereka yang hanya ingin hidup tenang, tapi harus kehilangan rumah, keluarga, bahkan rasa aman.
Namun sejarah tidak pernah berhenti di satu titik.
Ketika tsunami meluluhlantakkan Aceh pada Desember 2004, seluruh dunia menoleh ke ujung barat Indonesia itu. Di tengah puing-puing dan air mata, bencana itu justru membuka jalan bagi sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil: perdamaian.
Baca juga: Menakar Toleransi dan Keberagaman di Banda Aceh
Dua pihak yang bertahun-tahun berkonflik akhirnya duduk satu meja, bukan karena saling setuju, tetapi karena menyadari bahwa tidak ada kemenangan sejati dalam perang saudara.
Lalu lahirlah Perjanjian Helsinki pada tahun 2005 — kesepakatan yang mengakhiri konflik bersenjata dan membuka lembaran baru bagi Aceh. Bukan berarti semuanya langsung berubah.
Proses rekonsiliasi tidak secepat gencatan senjata. Rasa percaya harus dibangun ulang, luka-luka lama harus diobati dengan keadilan, dan ruang demokrasi harus diberikan agar suara rakyat benar-benar didengar.
Hari ini, Aceh telah banyak berubah. Tidak lagi ada suara tembakan di tengah malam. Tidak ada lagi razia yang membabi buta. Namun perjuangan belum selesai. Damai bukan hanya soal tidak ada perang, tapi juga tentang keadilan yang merata, pembangunan yang inklusif, dan ruang untuk semua suara — bahkan yang berbeda sekalipun.
Sebagai generasi yang tidak mengalami langsung masa DOM, kita punya tanggung jawab moral untuk menjaga damai ini tetap hidup. Dengan mengenang, kita belajar. Dengan belajar, kita mencegah. Karena masa lalu yang dilupakan adalah benih bagi konflik yang sama di masa depan.
Aceh mengajarkan kita bahwa perdamaian itu mungkin — jika ada keberanian untuk berdialog, kesediaan untuk mendengarkan, dan tekad untuk berubah.
Penulis: Riskia Ananda Putri, mahasiswa prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.