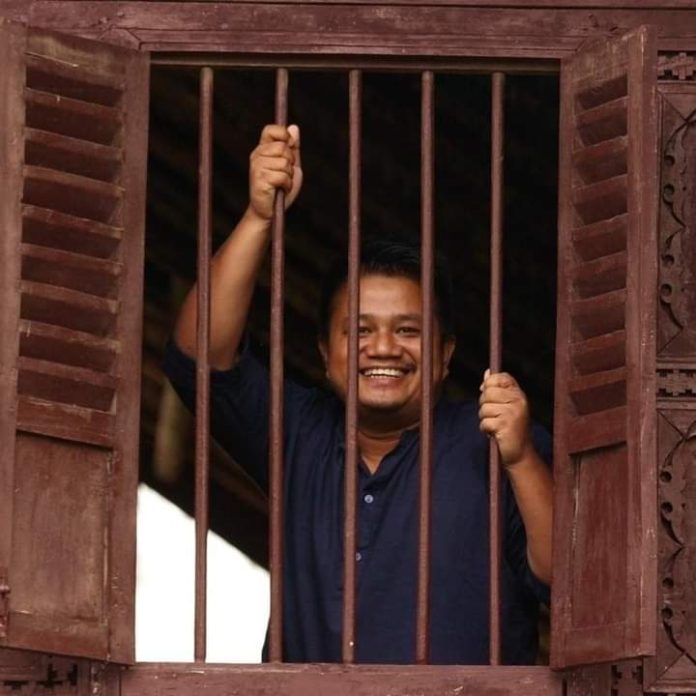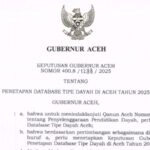Seorang anak petani miskin, yatim sejak usia 8 tahun, setelah puluhan tahun kemudian telah menjadi niagawan penting. Ia yang dulu bukan siapa-siapa, kini telah menjadi orang penting.
Sebut saja namanya A. Seorang pria yang hidup melarat sedari kecil. Ia tak tahu arti kemewahan ketika belia hingga remaja. Bahkan membayangkannya saja A tidak berani.
“Sebagai anak petani miskin, hidup terlalu sulit saat itu. Satu-satunya tumpuan hanya ibu yang menggarap petak sawah kecil di kampung udik yang tak berlistrik,” sebut A pada sebuah kesempatan. “Ayah hanya meninggalkan sedikit tanah yang kami faraiz setelah beliau meninggal. Selebihnya hanya karisma sebagai tokoh legendaris di kampung.”
Baca: Aceh Utara Jeut Cheih Asai Bek Choih
A meniti langkah secara alamiah. Ia bersekolah tanpa mengharap suatu saat menjadi sesuatu. Baginya, sekolah merupakan keharusan, supaya tak tertolak oleh zaman. Tanpa banyak drama, ia menuntaskan SMA di kota yang jauh dari rumah ibunya.
A remaja ingin melanjutkan kuliah. Tapi seluruh keluarga tak yakin mereka dapat memberikan dukungan material. A juga bandel untuk ukuran pemuda tanggung yang ingin kuliah. Ia “tak lurus” karena kerap mbalelo menurut orang lebih tua.
Namun anak petani miskin itu tak peduli. Ia mendaftar pada sebuah institut. Ia memilih jurusan Teknik Sipil. Tak seorangpun dari keluarganya ia beritahu. Setelah lulus seleksi masuk, ia menumpang pada kost seniornya di dekat kampus.
Semester pertama ia lalui dengan penuh perjuangan. Menjual produk untuk kalangan terbatas. Pasar yang ia target berupa ruang niaga dengan konsumen yang tidak banyak drama. Bisnis itu lancar, tapi pasarnya tak dapat lagi diperluas. Biaya pendidikan semakin tinggi. Ia cari cara baru.
Setahun kemudian ia banting setir. Mulai berniaga jasa joki, les privat masuk sekolah favorit, hingga bisnis kecelakaan. Siapa saja yang butuh surat celaka supaya dapat mengklaim asuransi, dapat menemui A. Semua jejaring diservis dengan bagus. Mulai “korban”, biro keuangan, hingga klinik kesehatan. Dari sana pundi-pundi rupiah mengalir deras. Cukup mewah untuk ukurannya sebagai mahasiswa.
A tahu bisnis yang ia geluti hanya sebatas jembatan semata. Sekadar dapat membayar biaya kuliah dan sisanya untuk belanja isi lambung. Apa yang ia jadikan pondasi ekonomi tidak menjanjikan masa depan bagi dirinya.
Tahun ketiga dia banting setir lagi. Hanya fokus pada jasa joki yang lebih meyakinkan. Pun demikian itu hanya side jobs. Tetap dilakukan karena banyak mahasiswa lain bergantung hidup dari bisnis perjokian.
Sejak mendaftar kuliah, ia telah punya mimpi. Menjadi orang penting. Ia benar-benar belajar berbagai mata kuliah kejuruan di institutnya. Ia tahu bila kelak lulus, dunia usaha membutuhkan ahli madya terampil. Bukan semata bermodal ijazah. Ia tak tertarik menjadi pegawai negeri. Karena dunia birokrasi saat itu tidak menantang. Siapa saja bisa menjadi pegawai negeri asal mau dan ada orang dalam. Ia mau menjadi orang besar dengan karya besar.
“Dunia sektor profesional tak mau tahu kita anak siapa. Mereka tak peduli saya anak petani atau anak pegawai. Industri membutuhkan tenaga terampil. Dunia bisnis swasta beda dengan bisnis pemerintah. Mengapa banyak BUMN merugi, karena mereka memasukkan ular ke dalamnya. Mengapa nyaris tak ada BUMD yang besar, karena peluang kerja dibuka untuk menampung kolega. Dunia bisnis murni yang dibangun oleh pengusaha, membutuhkan tenaga terampil. Saya berhasil masuk karena itu. Terampil,” sebut A yang berkali-kali menyebut diri anak petani.
Setelah lulus kuliah, ia bukan lagi anak petani miskin. Tapi berubah menjadi karyawan berdedikasi. Satu persatu proyek besar berhasil ia laksanakan tanpa cacat. Ia menjaga trust dari mitra bisnis. Namanya melambung. A menjadi lelaki yang berintegritas dalam tiap proyek-proyeknya. Kiprahnya terus meluas. Ia sukses membangun diri.
Ketika ia kecil, di kampungnya ada seorang pria terpandang. Kaya untuk ukuran warga di sana. Tapi orang kaya itu sepertinya tidak menganggap pendidikan sebagai aset masa depan. Mungkin juga anak-anaknya tidak mau sekolah tinggi karena telah nyaman dengan situasi serba berkecukupan.
Kini mereka secara ekonomi berada jauh di bawah A. Bahkan beberapa bekerja pada A sebagai karyawan lapangan.
Demikian juga beberapa kenalan A di jurusan berbeda. Mereka kuliah tanpa harus berpikir di mana harus mencari uang. Setiap bulan mendapatkan kiriman uang yang banyak. Karena “nyaman” akhirnya tidak serius belajar, juga tak sempat bergaul dengan lintas jejaring. Mereka terlalu sibuk menghabiskan waktu dan uang di lapak judi. Beberapa lainnya membinasakan waktu bergonta-ganti pacar. Akhirnya pacar dinikahi pria lain, si teman tak jadi orang.
Mendengar kisah A saya teringat cuplikan pernyataan bahwa kesulitan melahirkan petarung yang tak punya kata kalah. Berkali-kali jatuh tetap berdiri lagi. Selama mimpi belum dicapai, ia akan terus bertempur. Kelak ia berhasil. Darinya akan lahir generasi penikmat. Bila salah dikelola, generasi penikmat akan menjadi penerus yang lemah. Contohnya sudah terlalu banyak.
Saya juga terkenang pada sebuah diskusi dengan seseorang yang mengatakan bila ada 100 pintu kesuksesan, 99 di antaranya hanya dapat dibuka oleh yang berpendidikan tinggi. Hanya 1 untuk orang-orang “ajaib” yang sukses hanya dengan cara-cara tradisional.