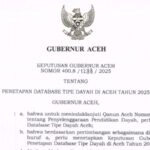Hutan Gle Mongmong di pedalaman sebuah kawasan di Aceh dikenal warga sebagai tempat yang tak boleh dimasuki selepas Ashar.
Bukan karena binatang buas, tapi karena sesuatu yang disebut orang tua-tua sebagai ureung gle, makhluk penjaga bukit yang bukan manusia, bukan pula hewan, tapi sesuatu di antara keduanya. Warga desa hanya menyebutnya dengan berbisik, seolah menyebutnya terlalu keras bisa membuatnya datang.
Namun Rijal dan dua temannya, Fathan dan Zikri, tidak percaya cerita seperti itu. Mereka adalah pemuda kota yang datang ke pedalaman untuk sebuah pekerjaan survei tanah. Ketika warga memperingatkan mereka agar tak masuk hutan selepas sore, mereka justru tertawa
Baca: Bercinta dengan Kuntilanak
“Masuk bentar aja, Teungku. Foto lokasi, pulang. Mana ada hantu,” kata Fathan sambil membawa kamera.
Warga yang menahan mereka hanya menggeleng. “Kamu belum tau. Di sini… kalau sudah masuk azan Magrib, lebih baik jangan lagi lihat ke belakang. Apa pun yang kamu dengar,jangan balas.”
Mereka menganggapnya hanya tradisi menakut-nakuti.
Sore itu mereka masuk hutan Gle Mongmong. Matahari sudah menyentuh ujung pepohonan, menandakan waktu Magrib tinggal sebentar. Namun Rijal, yang paling keras kepala, tetap melanjutkan.
“Tinggal lima menit jalan lagi,” katanya.
Hutan itu terasa lebih dingin dari seharusnya. Pepohonan saling merapat, menyisakan cahaya yang semakin redup. Zikri mulai gelisah.
Baca: Misteri Kematian Nek Jah
“Ji… kita balik saja. Suasananya nggak enak.”
Namun sebelum Rijal sempat menjawab, terdengar suara ranting patah dari belakang mereka—keras, seperti ada sesuatu besar melangkah. Mereka spontan menoleh. Kosong.
“Kucing hutan mungkin,” kata Fathan, walau suaranya bergetar.
Mereka melanjutkan, tetapi langkah mereka belum jauh ketika suara desahan panjang terdengar di kiri mereka.
“Uuhhhh… uuhhh…”
Zikri menelan ludah. “Itu… bukan kucing.”
Rijal berusaha tegar. “Angin.”
Namun tiba-tiba, dari balik semak, muncul kepala manusia—atau sesuatu yang menyerupainya—mengintip setinggi pinggang mereka. Rambutnya panjang dan kotor. Matanya hitam seluruhnya. Dan kulitnya pucat berlumur lumpur.
Makhluk itu mengeluarkan suara seperti orang menjerit tercekik.
“—Eeeeeeeekkkk—!!”
Ketiganya menjerit bersamaan dan lari.
Matahari sudah tenggelam. Hutan gelap total. Senter mereka menjadi satu-satunya harapan.
“Ke… kenapa kita nggak keluar dari tadi…” gumam Zikri sambil terengah.
Fathan, yang merekam sebagian perjalanan, menoleh ke belakang. “Tunggu… kalian dengar itu?”
Suara langkah cepat terdengar mengikuti mereka. Bukan satu, tapi seperti banyak kaki.
DUMDUMDUMDUM
Mereka mempercepat langkah. Suara itu semakin mendekat. Lalu tiba-tiba berhenti.
Hening.
“Sudah jauh mungkin,” kata Rijal.
Lalu,
TARAAAK!!
Sebuah batang pohon besar terjatuh tepat di belakang mereka, hampir mengenai punggung Rijal. Seolah sesuatu menendangnya dari samping.
“LARI!!”
Mereka berlari tanpa arah.
Hutan terasa semakin sempit. Kabut turun cepat, padahal ini bukan musimnya. Mereka tak lagi tahu arah pulang. Suara adzan dari desa tak terdengar.
Tiba-tiba Zikri memekik.
“SENTERKU MATI!”
Dan dalam gelap itu mereka mendengar bisikan-bisikan yang datang dari semua arah.
“Pulanglah.”
“Sudah kami tunggu.”
“Tinggal sedikit lagi.”
Fathan menyalakan kamera untuk cahaya. Saat lampu kamera menyala, ia mengarahkan ke kiri—dan menjerit histeris.
Di balik dua pohon besar, terdiri beberapa sosok kecil seperti anak-anak, namun tubuhnya terlalu kurus, matanya cekung gelap, dan mulutnya sobek sampai ke telinga. Mereka bergerak kaku, serempak, seperti sedang meniru cara manusia berjalan.
Tiba-tiba mereka berlari dengan kecepatan tak wajar menuju kelompok itu.
“AAAAA!!!”
Ketiganya berlari kacau. Kamera Fathan terjatuh.
Setelah beberapa menit berlari, mereka tiba di sebuah rawa kecil. Airnya hitam, tenang, namun menyebarkan bau tajam tanah basah. Mereka terjebak; tak ada jalan lain.
Suara itu terdengar lagi—lebih dekat. Banyak. Ratusan langkah kecil, cepat, berhamburan dari segala penjuru.
Fathan gemetar hebat. “Ji… itu apa?! APA?!”
Rijal hanya bisa menggeleng sambil meneteskan air mata.
Tiba-tiba, dari balik pepohonan depan mereka, muncul sosok besar. Tingginya hampir dua kali manusia, tubuhnya diselimuti lumut dan tanah seperti bagian dari bukit itu sendiri. Wajahnya samar, namun dua lubang hitam besar tampak seperti mata yang siap menelan apa saja.
“Ureung gle…” bisik Zikri, suaranya hampir tak keluar.
Makhluk itu membuka mulutnya—terlalu lebar untuk ukuran manusia—dan mengeluarkan suara gemuruh.
“Puuuuulang… kalian… terlambat…”
Tanah di sekitar mereka bergetar. Air rawa mulai mengalir seperti disedot ke bawah.
Fathan, panik, berlari ke sisi kiri—namun sepasang tangan kurus muncul dari tanah, menarik kakinya.
“JANGAN—JANGAN!!! RIIJAAALL!!”
Rijal dan Zikri mencoba menariknya, namun semakin mereka menarik, tangan-tangan itu semakin banyak. Puluhan tangan kecil, kotor, berlumpur, keluar dari tanah dan meraih tubuh Fathan.
Dalam sekejap, Fathan terseret masuk ke lumpur. Teriaknya memanjang, lalu menghilang.
Rijal dan Zikri terdiam beberapa detik sebelum kembali lari.
Mereka tiba di dataran tinggi kecil. Napas tersengal, tubuh gemetar. Rijal menyalakan senter terakhir.
Tepat saat cahaya muncul, bayangan wajah pucat muncul hanya lima sentimeter di depan senter.
Zikri menjerit.
Sosok itu—wanita dengan rambut gimbal, mata hitam, dan gigi tajam—menggantung terbalik dari dahan pohon. Tiba-tiba ia menjatuhkan diri ke arah Zikri sambil menjerit memekakkan telinga.
Zikri jatuh pingsan.
Rijal menariknya, namun suara ribut datang dari belakang: ratusan makhluk kecil itu kembali muncul dari kabut. Mereka bergerak cepat, melingkari mereka dari segala arah.
Rijal menggendong Zikri dan berlari sekuat tenaga. Tapi saat ia hampir mencapai jalur turun bukit, tanah di bawahnya runtuh. Ia terperosok ke dalam lubang dangkal.
Saat ia mencoba berdiri kembali, ia menyadari sesuatu: Zikri tidak bergerak.
Mulut Zikri terbuka, namun bukan mengeluarkan napas…
melainkan tanah. Tanah keluar dari tenggorokannya, seolah ada sesuatu merangkak masuk ke dalam tubuhnya.
Lalu Zikri membuka mata. Hitam seluruhnya.
“Pulanglah bersamaku…”
Apa yang terjadi selanjutnya tidak pernah jelas. Rijal ditemukan tiga hari kemudian oleh warga desa, tertelungkup di tepi hutan, tubuh penuh lumpur. Ia masih hidup, tetapi tatapannya kosong selama-lamanya, dan setiap malam ia hanya menggumamkan satu kalimat,
“Jangan lihat ke belakang… jangan lihat…”
Fathan dan Zikri tak pernah ditemukan.
Dan hutan Gle Mongmong tetap berdiri, menunggu siapa pun yang berani masuk selepas Magrib. Makhluk-makhluk itu tak pernah pergi. Mereka hanya menunggu.
Catatan: Cerita ini hanya bersifat khalayan belaka. Bila ada terdapat kesamaan tempat, tokoh, dan jalan cerita, hanya kebetulan semata.