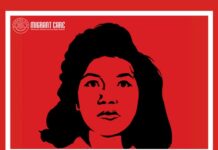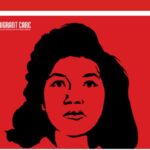Tes Kemampuan Akademik merupakan langkah awal untuk membangun sistem evaluasi pembelajaran yang transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada perbaikan. Ia harus dirancang dengan prinsip kesetaraan, diimplementasikan dengan empati, dan ditindaklanjuti dengan program konkret.
***
Di tengah hiruk pikuk pembicaraan tentang pendidikan bermutu, suara dari daerah tertinggal kerap sayup terdengar. Padahal, di sanalah tantangan pendidikan nyata bermukim, baik itu keterbatasan guru, sarana prasarana yang minim, maupun kualitas pembelajaran yang belum merata.
Laporan Profil Pendidikan Indonesia 2023 yang dirilis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat bahwa lebih dari 70 persen sekolah di wilayah tertinggal menghadapi tantangan infrastruktur dan kekurangan guru bersertifikasi.
Maka, ketika Kemendikbudristek menggulirkan kebijakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai sistem evaluasi pembelajaran nasional pada tahun 2025, sebagai guru kita menyambutnya dengan optimisme.
Melalui Tes Kemampuan Akademik kita yakin ini menjadi momentum yang benar-benar dan menjadi alat pemerataan mutu pendidikan, bukan hanya sekadar pengukur prestasi akademik siswa. Di sinilah peran semua pemangku kepentingan—termasuk media—untuk mengawal pelaksanaannya secara adil dan kontekstual, terutama untuk daerah-daerah yang selama ini tertinggal dalam banyak hal.
Dan sebagai pemerhati pendidikan di daerah, saya melihat bahwa sistem evaluasi selama ini terlalu beragam dan sangat bergantung pada subjektivitas sekolah. Tidak semua sekolah punya sumber daya yang mumpuni untuk menilai capaian pembelajaran secara komprehensif.
Sebuah studi oleh OECD (Education Policy Outlook: Indonesia, 2022) menyebutkan bahwa perbedaan pendekatan penilaian antar sekolah memperlebar ketimpangan hasil belajar antarwilayah.
Baca juga: Guru Harus Sehat
Dengan hadirnya TKA, yang digagas oleh Kemendikdasmen, terlihat bahwa negara mulai mengambil alih peran pentingnya yakni dengan menyediakan alat ukur standar, adil, dan setara bagi semua sekolah.
TKA bukan sekadar ujian, melainkan instrumen untuk evidence-based policy. Data dari TKA bisa digunakan pemerintah pusat dan daerah untuk melihat wilayah mana yang tertinggal, kompetensi apa yang lemah, dan intervensi seperti apa yang dibutuhkan.
Misalnya, jika hasil TKA di satu kabupaten menunjukkan skor numerasi siswa kelas 6 sangat rendah, maka pemerintah daerah bisa segera menurunkan program pelatihan guru matematika, memperkuat modul pengayaan, dan menambah jam belajar tematik.
Pendekatan ini sejalan dengan temuan jurnal Indonesian Journal of Educational Review (Vol. 10 No. 1, 2023) yang menyimpulkan bahwa intervensi berbasis data hasil asesmen meningkatkan efektivitas pelatihan guru hingga 30 persen dibanding pendekatan umum.
Kebijakan TKA juga menyiratkan pesan kuat tentang pentingnya kesetaraan akses terhadap pendidikan berkualitas. Di daerah tertinggal, siswa tidak hanya tertinggal secara geografis, tetapi juga digital.
Survei yang dilakukan oleh AIPI dan Program INOVASI pada 2022 mengungkapkan bahwa empat dari 10 sekolah di wilayah 3T belum memiliki akses internet yang layak, sementara 60 persen guru mengaku belum terbiasa menggunakan platform digital pembelajaran.
Namun, TKA berbasis teknologi bisa menjadi pintu masuk akselerasi transformasi digital. Ketika sekolah dipersiapkan untuk menyelenggarakan TKA, maka infrastruktur, pelatihan, dan bimbingan teknis akan ikut mengalir. Inilah efek domino positif yang dibutuhkan.
Agar tidak menjadi beban tambahan, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk menyiapkan perangkat dan SDM. Bahkan lebih dari itu, partisipasi masyarakat, LSM pendidikan, dan sektor swasta harus ikut bergerak—karena pendidikan bukan kerja satu arah, tapi kolaborasi.
TKA akan berhasil jika diletakkan dalam kerangka besar pembelajaran yang berpusat pada murid. Evaluasi seharusnya bukan untuk menilai siapa yang pintar dan siapa yang tidak, tetapi untuk melihat siapa yang butuh dibantu dan bagaimana cara membantunya. Prinsip ini selaras dengan arah Kurikulum Merdeka yang menekankan asesmen sebagai alat refleksi pembelajaran, bukan klasifikasi murid.
TKA juga bukan “cap nilai nasional” yang menekan guru atau siswa, melainkan alat refleksi dan pemicu perbaikan. Setiap data harus diterjemahkan menjadi aksi nyata. Misalnya, sekolah dengan hasil rendah harus diberi pendampingan, bukan stigma.
Guru-guru perlu diberdayakan untuk memahami data hasil TKA, bukan sekadar menerima laporan. Laporan UNICEF Indonesia menegaskan bahwa asesmen yang digunakan secara bijak dapat memperkuat peran guru sebagai agen perubahan, bukan hanya pelaksana kurikulum.
TKA adalah langkah awal untuk membangun sistem evaluasi pembelajaran yang transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada perbaikan. Ia harus dirancang dengan prinsip kesetaraan, diimplementasikan dengan empati, dan ditindaklanjuti dengan program konkret.
Namun, ada satu hal penting yang tidak boleh dilupakan: data hanyalah awal dari perubahan, bukan perubahan itu sendiri. Yang lebih menentukan adalah keberanian kita—pemerintah, pendidik, masyarakat—untuk menindaklanjuti data itu dengan kebijakan dan tindakan nyata. TKA hanya akan berarti jika menjadi dasar penyusunan anggaran pendidikan yang lebih adil, perekrutan dan pelatihan guru yang lebih strategis, serta penyediaan fasilitas yang benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Lebih dari sekadar angka di atas kertas, TKA seharusnya menjadi cermin yang jujur tentang kondisi pendidikan kita—dan dari sana, lahirlah tekad untuk memperbaikinya, bersama-sama.
Sebagai orang yang melihat langsung denyut pendidikan di pelosok, saya percaya bahwa anak-anak dari Aceh, Nusa Tenggara, Papua, hingga Maluku memiliki hak yang sama untuk bermimpi dan berkembang. Tes Kemampuan Akademik bisa menjadi jembatan menuju keadilan itu—asal kita tak hanya mengukurnya, tapi juga mengubahnya menjadi aksi nyata.
Karena pada akhirnya, kualitas pendidikan Indonesia tidak ditentukan oleh skor tertinggi di kota besar, tapi oleh seberapa kuat kita mengangkat yang paling tertinggal agar bisa maju bersama.